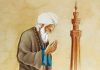JIC- Sebelum tahun 1859, tidak tersedia data yang jelas mengenai jumlah orang Arab yang bermukim di Hindia Belanda yang menjadi jajahan Belanda. Di dalam catatan statistik resmi pemerintah kolonial, keberadaan mereka dirancukan dengan orang Bengali dan pendatang lain yang beragama Islam.
Situasi ini berubah (mulai 1870), seiring dengan perkembangan pesat teknologi perkapalan sehingga perpindahan orang dari Hadramut menjadi lebih mudah. Maka, pada tahun-tahun itulah awal dari masa yang sepenuhnya baru bagi koloni-koloni Arab yang ada di Indonesia.
Jadi, sebelum diterbitkannya data statistik resmi tersebut, saat itu mengenai jumlah orang Arab di nusantara, khususnya di Jawa, hanya diperoleh dari keterangan kira-kira yang berasal dari cerita orang tua dan tradisi setempat.
‘’Hasil penelitian saya mengenai hal itu menunjukkan bahwa orang Arab Handramaut mulai datang secara massal ke nusantara pada tahun-tahun terakhir abad XVIII. Perhatian mereka yang pertama adalah Aceh. Dari sana mereka memilih pergi ke Palembang dan Pontianak,’’ tulis LWC van den Berg, penulis buku klasik yang berjudul, Orang Arab di Nusantara.
Orang Arab mulai banyak menetap di Jawa setelah tahun 1820 dan koloni-koloni mereka di bagian timur Nusantara pada 1870. Data statistik pada tahun itu, tercatat jumlah populasi orang Arab dan keturunannya sudah mencapai 10.888 orang. Di Batavia, misalnya, ada 952 orang, Cirebon 816 orang, Tegal 204 orang, Cirebon 816 orang, Pekalongan 608 orang, Semarang 358 orang, dan Surabaya (mencakup Keresidenan Surabayam Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Sidayu) mencapai 1626 orang. Lalu, Yogyakarta 77 orang, Surakarta 42 orang, Madura 979 orang, Kedu (Magelang) 47 orang, Cilacap 7 orang, Purwokerto 3 orang, dan Purbalingga 4 orang.
Koloni Arab di Jawa dan Batavia
Menurut Berg, dari tabel statistik yang terbit pada 1885, saat itu di Pulau Jawa terdapat enam koloni besar Arab, yaitu Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Di Madura hanya satu, yaitu di Sumenep. Setiap koloni punya ciri khasnya tersendiri.
Koloni di Batavia sudah merupakan koloni terbesar di nusantara, jika dimasukkan anggotanya yang lahir di Arab. Namun, baru pada 1884 koloni ini menjadi begitu besar sehingga pemerintah Belanda mengharuskan adanya kepala koloni.
Sebelumnya, orang Arab berada dalam koloni-koloni kecil menetap di wilayah pribumi, terutama di wilayah yang ditinggali orang-orang Benggali, yang dalam bahasa Melayu disebut Pekojan, artinya “tempat tinggal Kojah” (Kojah berasal dari bahasa Persia “Khawajah” berati Benggali, atau lebih tepat penduduk asli Hindustan).
Lama kelamaan orang-orang Benggali digantikan orang Arab. Di Pekojan, hanya terdapat beberapa orang Cina dan sejumlah besar pribumi, seperti juga di semua wilayah Arab.
Rumah mereka terbuat dari batu bata dan bergaya sama dengan rumah di wilayah Eropa yang terdapat di Kota Batavia tua. Satu-dua rumah yang menggunakan balkon tertutup memperlihatkan kebangsaan penduduknya. Wilayah Pekojan sangat kumuh, tapi tampaknya orang Arab tidak terlalu menderita karenanya.
Di sana berdiri sebuah masjid yang luas dan seorang imam Arab yang sekaligus menjadi kepala sekolah. Salah satu ruangan di lantai dasar dijadikan kelas. Bangunan itu disebut dengan nama Melayu, “Langgar”, dan membentuk wakaf yang makmur.
Namun, untuk shalat Jumat tidak dilakukan di Langgar, orang Arab melakukannya di masjid pribumi yang lebih besar yang terdapat di wilayah itu. Di samping langgar, di Pekojan masih terdapat masjid Arab lagi yang berukuran lebh kecil dan disebut “Zawiah”.
Suasana Koloni Arab di Batavia
Sebagian orang Arab tinggal di daerah pinggiran, seperti Krukut dan Tanah Abang. Namun, pada saat ini kehidupan mereka belum berkembang (maksudnya pada saat Berg melakukan kajian–Red).
Beberapa orang Arab yang lain menetap di wilayah lain, yakni di lingkungan pribumi. Di semua wilayah itu, mereka mendiami rumah yang bergaya sama dengan rumah pribumi, atau mereka yang kaya tinggal di rumah besar atau kecil yang bergaya vila.
Di Batavia didapati orang Arab yang berasal dari segala tempat di Hadramaut dan dari segala lapisan masyarakat. Hanya golongan “sayid” yang merupakan minoritas.
Sebagian besar orang Arab yang datang ke Pulau Jawa dan Singapura, terlebih dahulu singgah di Batavia, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Delapan tahun setelah itu (setelah adanya pendataan penduduk yang terakhir di 1884–Red), jumlah pendatang baru yang diizinkan masuk oleh Pemerintah Batavia, rata-rata jumlahnya melampui seratus orang untuk setiap tahunnya. Dan, sebagian pendatang baru ini kemudian menetap.
‘’Jadi, kelompok Arab di Batavia sedang berkembang dan jumlah anggotanya segera akan melampaui kelompok-kelompok lain,’’ tulis Berg ketika menganalisis perkembangan populasi penduduk di Batavia.
Sebagai akibat perkembangan itu, Berg kemudian meiihat bila di Batavia dijumpai hanya sedikit keluarga Arab yang turun- temurun telah menghuni nusantara. Sebagian besar orang Arab itu kawin dengan perempuan pribumi.
Kehidupan intelektual mereka tidak pula tinggi. Unsur Arab begitu menguasai keturunan campurannya sehingga mereka terpaksa belajar bahasa Arab untuk dapat berkomunikasi. Sebagai ciri khas wilayah Arab di Batavia, perlu dikemukakan sedikit adanya toko. Di Pekojan hanya terdapat tiga puluhan toko. Hampir seluruh perdagangan Arab di wilayah itu dilakukan dalam rumah melalui para penjaja.
Koloni Arab yang lain di Jawa, misalnya, relatif baru. Di Cirebon, baru pada 1845 koloni Arab di sana menjadi cukup besar sehingga dibutuhkan kepala koloni yang akhirnya menjadi kepala semua orang Arab di karesidenan itu. Baru pada 1872, koloni Arab di Indramayu dipisahkan dari koloni Arab Cirebon dan memiliki kepala koloni sendiri.
Koloni Arab di Cirebon dan Tegal
Seperti juga di Batavia, wilayah yang dihuni orang Arab, di Cirebon, semula wilayah orang Benggali dan merekalah yang membangun masjid yang sekarang dikenal sebagai “Masjid Arab”. Bangunannya cukup luas, tapi kurang terpelihara, seperti juga keadaan seluruh wilayah Arab. Jarang sekali ditemukan rumah-rumah yang cantik.
Koloni Arab di Cirebon hidup miskin. Satu-satunya orang Arab yang menjadi grosir di kota itu malah bangkrut. Di sepanjang jalan yang tampak hanyalah deretan toko-toko kecil, yang kotor dan tak lengkap isinya, dan tak satu pun menunjukkan kemakmuran pemiliknya, seperti yang terlihat di Pecinan.
Di antara koloni Arab yang besar di nusantara, koloni Arab Tegal adalah yang terbaru. Sebelumnya, hanya terdapat satu-dua keluarga dan kadang-kadang ada yang mampir sebentar di sana. Kepala koloni yang pertama diangkat pada 1883. Sejak zaman itu, jumlah orang Arab yang sebagian besar anggota suku Nahd, Kasir, dan Yafi, terus meningkat. Dan, sebagian wilayah Arab di Tegal setelah adanya imigrasi itu benar-benar menjadi padat.
Sejumlah rumah di Koloni Arab di Tegal ditinggali dua sampai tiga orang keluarga. Toko sangat sedikit, sebagian besar di antara orang Arab tinggal di gubuk yang dikelilingi kebun sayur dan hampir semuanya terkesan kotor dan miskin.
Koloni Arab di Tegal tampaknya lebih sedikit melaksanakan ibadah Islam dibandingkan koloni-koloni Arab yang lain yang pernah saya kunjungi. Hal ini tidak mengherankan mengingat asal usul mereka. Jarang ada orang Arab yang turut berjamaah di masjid pribumi, sementara dunia ilmu, tak seorang pun (di antara mereka–Red) meminatinya.
Sumber ; republika.co.id